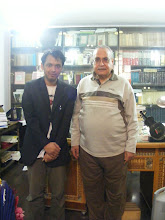Oleh Ahmad Hadidul Fahmi
Fakhr al-Din al-Razi lahir di Kota Ray, Iran pada tahun 544 H. Garis keturunannya bersambung pada Abu Bakar al-Shiddiq, shahabat kepercayaan Nabi Saw. Ayahnya adalah Dliya’ al-Din Umar, pembesar Syafi’iyyah sekaligus Asy’ariyyah pada masa itu. Ia mempunyai kitab terkenal bertajuk Ghayât al-Marâm fî Ilm al-Kalâm. Ayahnyalah yang kemudian membentuk karakter keilmuan al-Razi. Kota Ray memang dikenal mencetak banyak sarjana besar. Kita mengenal sufi,Abu Zakariya Yahya bin Mu’adz al-Razi (w. 258 H), kemudian dokter sekaligus filsuf besar, Abu Bakar Muhammad bin Zakariya al-Razi (w. 311 H), pakar bahasa, Abu al-Husayn Ahmad bin Faris al-Razi (w. 315 H), pakar hadis, Ibnu Abi Hatim al-Razi (w. 327 H), pakar fikih Hanafi, Abu Bakar al-Razi al-Jashshash (w. 370 H), Muhammad bin Abi Bakr al-Razi dan Quthb al-Din al-Razi. Masa al-Razi ini diumpamakan seperti masa al-Makmun dari segi dinamika intelektual—walaupun grafik keemasan Islam pada waktu itu sudah menurun. Oleh karena itu kita mengenal banyak sarjana besar yang semasa dengan al-Razi, seperti Ibnu Rushd (w. 595 H), al-Suhrawardi (w. 587 H), Ibnu Arabi (w. 638 H), dan Abd al-Qadir al-Jilani (w.561 H).
Ia berkeliling ke pelbagai negeri dalam menimba ilmu. Seperti perjalanan pertamanya ke Semnan dan Maragheh, Iran. Selain dikenal pengikutnya banyak, ia juga dikenal banyak musuh. Hal itu karena al-Razi kerap berkeliling dunia untuk menantang musuh-musuhnya berdebat dan berdialog. Seperti perjalanan al-Razi ke Khawarizmi untuk berdebat dengan Muktazilah, sampai akhirnya ia diusir dari sana. Perjalanan intelektual al-Razi untuk berdebat terekam dalam autobiografi yang diberi nama Munadzârât al-Râzi fi Bilâdi Mâ warâ’a al-Nahr, atau perdebatan al-Razi di Transoxania. Menurut Shalih al-Zirkan, perdebatan ini terjadi antara tahun 580 dan 590 H. Ia memasuki Bukhara, Samarqand, Khujand, kemudian menantang para pembesar di daerah tersebut untuk berdiskusi di depan umum. Tema yang didiskusikan berkaitan dengan fikih, ushul fikih, kalam dan filsafat. Ada nuansa keangkuhan tatkala al-Razi mensifati para pembesar di masing-masing daerah. Sebagaimana ketika ia menggambarkan Ridla al-Naysaburi, lawan debatnya di Bukhara, dengan perkataan, "ia terlalu banyak berpikir, tetapi sedikit bicara." Dan menghina al-Nur al-Shabuni di depan umum dengan ungkapan, "saya menganggap Anda bukan bagian orang-orang yang berpikir rasional, lebih-lebih untuk menganggap Anda bagian dari orang-orang hebat dan ulama."
Lepas dari itu, ketinggian intelektualitas al-Razi tak ada yang meragukan. Bagaimana tidak, dalam perkataannya, "demi Tuhan, saya khawatir di waktu makan tidak bisa menyibukkan diri dengan urusan ilmu. Karena sesungguhnya waktu dan zaman berharga", menunjukkan al-Razi merupakan tokoh yang ‘tergila-gila’ dengan ilmu. Karena ini, karangan al-Razi hampir mencapai nominal seratus. Karangan-karangan al-Razi yang sampai pada generasi sekarang, menyiratkan penguasaannya yang mendalam terhadap pelbagai disiplin ilmu. Al-Razi menguasa sejarah, ushul fikih, fikih, filsafat, ilmu kalam, kimia, kedokteran, bahkan ilmu sihir—dalam bukunya al-sirr al-maktûm. Al-Shafadi menuturkan, seperti dilansir Fathullah Khalif dalam bukunya Fakhr al-Din al-Râzi, metodologi al-Razi dalam menulis sebuah karya adalah dengan menyebutkan satu masalah, kemudian memunculkan klasifikasi dari setiap permasalahan, dan bagian-bagian yang merupakan perpanjangan dari klasifikasi tersebut. Al-Razi mempergunakan penyelidikan (al-sabr) dan klasifikasi (al-taqsîm) untuk menguatkan argumentasinya. Akan tetapi, menurut al-Shafadi lagi, metode ini mempunyai cela karena mempergunakan redaksi yang teramat ringkas. Bahkan al-Shafadi mengakui, ia terkadang tak mampu mengikuti alur pikiran al-Razi karena ringkasnya redaksi tulisan. Justru untuk memahami persoalan yang dilontarkan al-Razi, al-Shafadi kerap merujuk al-Ghazali di permasalahan yang sama.
II
Al-Razi belajar fikih pada ayahnya sendiri. Berdasarkan silsilah keilmuan yang ia tulis, berawal dari ayahnya (Dliya’ al-Din Umar), al-Baghawi (w. 516 H), al-Qadli al-Husayn al-Marwazi (w. 462 H), al-Qaffal (w. 417 H), Abi Zayd al-Marwazi (w. 371 H), Abi Ishaq al-Marwazi (w. 340 H), Abi al-Abbas bin Suraij (w. 306 H), Abi al-Qasim al-Anmathy (w. 288 H), Abi Ibrahim al-Muzani (w. 264 H), sampai pada Imam Syafi’i (w. 204 H). Menurut banyak sejarawan, dalam disiplin fikih, al-Razi mengarang sebuah buku yang menjabarkan kandungan (al-syarh) al-Wajîz karangan Abu Hamid al-Ghazali. Akan tetapi karangan ini dipercaya hilang karena tak sampai ke kita. Pandangan-pandangan fikihnya bisa dianalisa mempergunakan tafsirnya ensiklopedisnya, Mafâtih al-Ghaib, tatkala berbicara tentang ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan fikih. Atau bisa ditilik juga dari buku perdebatan al-Razi dengan ahli fikih Bukhara—dalam permasalahan jual beli—yang terekam dalam bukunya Munadzarat Fakhr al-Din al-Râzi. Permasalahan fikih yang sebenarnya cukup sederhana, di tangannya dimodifikasi dengan teori-teori filsafat yang cukup pelik dan sulit dicerna. Berdebat dengan Ridla Naysaburi, Ia mengatakan,
"perwakilan dalam jual beli mutlak tidak bisa dikatakan memiliki barang dengan unsur tipuan. Argumentasinya adalah, “mewakilkan untuk menjual sesuatu” tidak bisa mencakup “penjualan dengan tipuan dalam harga” (al-ghabn al-fahisy), tidak dari sudut pandang redaksi (lafadz) ataupun makna. Maka jual beli tidak sah. Saya mengatakan: mewakilkan tidak mencakup jual beli dengan tipuan, karena redaksinya “mewakilkan untuk menjual”. Dan mewakilkan untuk menjual bukanlah mewakilkan untuk penjualan yang dimaksud. Adapun redaksi mewakilkan untuk menjual (al-tawkîl bi al-bai’) sudah sangat jelas. Sedangkan mewakilkan untuk menjual bukanlah mewakilkan untuk penjualan yang dimaksud, alasannya, “menjual” mempunyai makna ganda bahwa yang dimaksud adalah menjual dengan harga sewajarnya, dan menjual dengan melakukan penipuan dalam harga (al-ghabn al-fahisy). Sedangkan Lafadz berhomonim (al-musyârakah), berbeda dengan lafadz yang bermakna beda (al-mubâyanah), serta tidak meniscayakan (al-musyârakah) terhadap al-mubâyanah. Maka jelas, bahwa perwakilan dalam jual beli tidak bisa merangkum jual beli dengan tipuan dalam harga."
Di sini al-Razi jelas memasukkan pembahasan ilmu logika dalam disiplin fikih. Persoalan yang dimunculkan adalah tentang hukum perwakilan dalam jual beli. Jika untuk jual beli mutlak (penjualan barang dengan mata uang), maka penjualan barang dengan tipuan dalam harga (al-ghabn al-fahisy) tidak termasuk di dalamnya. Ia mempergunakan metode perbedaan genus (al-jins) dan pembeda (al-fashl). Aplikasinya, jual beli adalah genus, yang di dalamnya terdapat jual beli dengan harga yang berlaku (bai’ bi al-mitsl), dan jual beli dengan tipuan dalam harga—yang kemudian disebut pembeda (al-fashl). Oleh karena itu, jual beli dengan tipuan dalam harga dengan sendirinya tidak bisa termasuk dalam jual beli mutlak, walaupun jual beli bisa mencakup jual beli yang mempergunakan tipuan dalam harga. Dengan kata lain, tesis tersebut akan meniscayakan setiap keumuman akan selalu didapat dengan kekhususan. Dan yang demikian tidak logis. Sebagaimana perkataan, “jika ini adalah hewan, maka pasti manusia—dalam standar pengertian manusia adalah hewan yang berakal.”
Sedang dari sudut pandang makna, al-Razi melanjutkan,
"Adapun tidak sah dari sudut pandang makna, dasarnya adalah, sebuah lafadz dikatakan bermanfaat jika menunjukkan ‘suatu hal’, oleh karena itu ‘hal tersebut’niscaya keluar dari esensi lafadz. Keniscayaan itu bersifat absolut dan berdasar kebiasaan, sebab, lafadz yang menunjukkan pada sebuah hal tentu saja memberikan faidah dari sudut pandang makna. Maka di sini terdapat dua perkara hilang.Dari sudut pandang makna, jual beli dengan tipuan dalam harga ‘bukan keniscayaan’ jual beli, sudah demikian jelas. Sebab, terminologi jual beli (al-bai’) merupakan lafadz yang mempunyai makna penjualan dengan harga wajar, dan penjualan dengan tipuan dalam harga. Lafadz yang bermakna ganda (homonim) tidak meniscayakan lafadz yang bermakna beda. Jika tidak, maka jika disebutkan lafadz berhomonim, akan selalu meniscayakan lafadz yang maknanya beda."
Dalam al-Mahshûl, al-Razi menjelaskan ketetapan di atas, sebagai berikut,
"permasalahan keenam, perintah untuk mengerjakan sebuah hal secara umum (mâhiyyah), tidak selalu berkonsekuensi menunjukkan perintah untuk hal-hal partikularnya (juz’iyyât). Seperti perkataan, ‘jual baju ini!’, tidak menunjukkan perintah ‘menjual baju dengan tipuan harga’ (al-ghabn al-fâhisy), atau ‘menjual dengan harga normal’ (al-bai’ bi al-mitsli). Sebab, kedua hal partikular (al-bay’ bi al-ghabn al-fâhisy dan baiy’ bi tsaman al-mitsli) ini termasuk dalam keumuman jual beli. Dan antara yang partikular sendiri niscaya berbeda satu sama lain […]. Jika demikian, maka perintah untuk mengerjakan ‘genus’ tidak meniscayakan perintah untuk mengerjakan ‘spesies’nya. Akan tetapi jika ada ‘kerelaan’ untuk melakukan praktek partikular (spesies)—dalam hal ini sebagai qarînah, maka keumuman lafadz bisa saja dibawa ke sana. Oleh karena itu kita mengatakan, ‘perwakilan dalam jual beli mutlak tidak bisa memiliki barang dengan penjualan jual beli tipuan, walaupun dikatakan memiliki barang dengan penjualan harga sewajarnya (al-bai’ bi al-mitsli) karena ada dalil yang menunjukkan kerelaan masyarakat terhadapnya—oleh karena kebiasaan."
Nalar al-Razi sebagai teolog, mendominasi pembahasan-pembahasan fikih dan selalu ditarik dalam pembahasan logika. Walaupun begitu, koridor berpikirnya masih dalam kerangka madzhab Syafi’i. Ia bahkan menulis biografi khusus Imam Syafi’i yang diberi nama Manâqib al-Imâm al-Syâfi’î, serta menjelaskan pelbagai permasalahan antar madzhab, kemudian menguatkan pendapat imamnya. Walaupun pada beberapa permasalahan, al-Razi kerap berbeda dengan Imam Syafi’i, seperti pada masalah ‘pengangkatan tangan’ dalam shalat dianjurkan di empat tempat—sedang Syafi’i di tiga tempat, ia sepakat dengan Abu Hanifah dalam kewajiban zakat buah-buahan dan tanaman, kewajiban witir, orang yang dahaga dan tidak menemukan air wajib minum khamr, dan melemahkan pandangan Imam Syafi’i yang melihat kewajiban penerima zakat terbatas di delapan kelompok yang disebutkan oleh al-Qur’an. Keberanian al-Razi untuk berbeda dengan Imam Syafi’i, tentu bertentangan dengan ungkapan Ibnu Taymiah yang mengatakan bahwa al-Razi termasuk sarjana Islam yang lemah dalam disiplin fikih. Ungkapan Ibnu Taymiah lebih karena fanatik sebab al-Razi mengarang buku tentang sihir. Bagi sebagian sarjana, Ibnu Taymiah tidak membaca lengkap seluruh karya al-Razi, tetapi anehnya, ia mempunyai keberanian menggeneralisasi kapabilitas intelektual al-Razi.
III
Thaha Jabir al-Ulwani menuturkan, bahwa kitab ushul fikih yang paling layak dikaji setelah al-Risalah Imam Syafi’i adalah al-Burhân karangan Imam Haramain, al-Mustashfâ karangan al-Ghazali—ketiganya dari Ahli Sunnah, al-‘Ahd karangan al-Qadli Abd al-Jabbar dan al-Mu’tamad karangan Abu Husayn al-Bashri—keduanya dari Muktazilah. Empat kitab ini mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain, sehingga bagi pengkaji ushul fikih, kerap merasa kesulitan jika harus mengkaji empat buku ini bersamaan. Fakhr al-Din al-Razi dan al-Amidi--melalui bukunya al-Mahshûl fi ‘Ilm al-Ushul dan al-Ihkam fî Ushûl al-Ahkâm —berusaha merangkum keempat kitab ushul babon tersebut. Karena tak dapat disangkal, bahwa al-Razi telah mendalami ushul fikih semenjak dini. Al-Razi telah hafal al-Mustashfâ karangan Abu Hamid al-Ghazali dan al-Mu’tamad buah tangan Abu Husain al-Bashri di awal karirnya. Karena ini, oleh para ahli tahkik dan sarjana ushul fikih, al-Razi digelari “al-Imam”.
Ia tak seperti al-Amidi, yang hanya merangkum keempat kitab di atas dalam al-Ihkâm. Tetapi meneliti dan mengkaji secara kritis tesis-tesis yang tertuang dalam keempat kitab babon tersebut. Al-Razi kerap melampaui capaian nalar Imam Haramain, al-Ghazali, Abdul Jabbar dan Abu Husain al-Bahsri di pelbagai permasalahan, dan meyakini pendapat yang baginya lebih kuat dan rasional secara independen. Oleh karena itu, hemat penulis, Al-Razi dalam kitabnya sebenarnya tak bisa dikatakan sepenuhnya menggabungkan keempat paradigma penulis kitab ushul fikih sebelumnya. Sebab, pada faktanya ia lebih banyak mengkritik pandangan-pandangan Muktazilah—dalam permasalahan parsial--dan mengunggulkan pandangan Madzhabnya—walaupun pada satu keadaan juga ia berani berbeda dengan al-Ghazali dan pada beberapa kecil permasalahan ia lebih sepakat dengan Muktazilah. Akan tetapi dalam skala mayoritas, al-Razi tak keluar dari metode berpikir madzhab Syafi’ dan Asy’ari.
Untuk mengidentifikasi karangan-karangan al-Razi, saya berhutang budi terhadap Thaha Jabir al-Ulwani. Al-Ulwani mencoba memilah karya-karya al-Razi yang diyakini benar-benar ditulis olehnya, ataupun yang diragukan sebuah karya benar-benar ditulis oleh al-Razi. Bahkan mencoba mengoreksi nama karya al-Razi yang dituliskan oleh sejarawan klasik, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan dan penyematan. Hal itu, misalnya, dilakukan oleh Haji Khalifah yang menyebut Durrat al-Tanzîl wa Ghurrat al-Ta’wîl sebagai karangan al-Razi dalam tafsir,padahal kitab tersebut karangan al-Khatib al-Iskafi (w. 421 H).
Selain al-Mahsûl, al-Razi mempunyai beberapa karangan dalam disiplin ushul fikih; pertama,Ibthâl al-Qiyâs.Tetapi buku ini belum selesai. Oleh karena itu, Dr. Mohammad Hassan dalam bukunya Fakhr al-Din al-Râzi memandang, al-Razi termasuk sarjana yang menolak argumentasi analogi (al-qiyâs) karena ia mempunyai buku yang spesifik menolak argumentasi analogi (al-qiyâs); kedua, Ihkâm al-Ahkâm. Ulwani mengatakan, al-Razi dalam karangan-karangannya yang lain tak pernah menyebut secara eksplisit terhadap buku Ihkâm al-Ahkâm ini. Buku ini merupakan buku al-Razi yang dipercaya hilang; ketiga, al-Jadal. Seperti didapatkan dari perpustakaan di Turki, buku ini lengkapnya berjudul al-Jadal wa al-Kâsyif ‘an Ushûl al-Dalâil wa Fushûl al-‘Ilal; keempat, Radd al-Jadal; kelima; al-Tharîqah fi al-Jadal; keenam, al-Tharîqah al-‘Alaiyyah fî al-Khilâf. Akan tetapi al-Ulwani meragukan penisbatan buku ini terhadap al-Razi; ketujuh,‘Asyrat Alâf nuktat fî al-Jadal; kedelapan, al-Ma’alim fî Ushûl Fiqh; kesembilan, al-Muntakhab atau Muntakhab al-Mahsûl. Buku ini merupakan ringkasan dari al-Mahsûl. Akan tetapi al-Ulwani meragukan penisbatan buku ini pada al-Razi; kesepuluh, al-Nihâyah al-Bahâiyyah fî al-Mabâhits al-Qiyâsiyyah.
Al-Mahshûl merupakan karya terpenting al-Razi dalam disiplin ushul fikih. Karya-karya ushul fikih yang ditulis sebelum al-Mahshûl, sudah terangkum dalam al-Mahshûl, sedangkan karya yang ditulis setelah al-Mahshûl, adakalanya ringkasan atau pilihan atas bagian-bagian penting dari al-al-Mahshûl. Kitab ini ditulis pada usia 32 tahun. Al-Razi merupakan sarjana ushul yang bercorak falsafi. Kita bisa melihat satu contoh dari pembahasan definisi “hukum syara’” yang mengindikasikan hal itu. Selesai mendefinisikan hukum Syara’, al-Razi menyebut potensi kritikan untuk definisi yang sudah disebutkan,
"jika dikatakan: definisi ini tidak logis karena empat hal. Pertama, jika demikian, maka hukum Allah adalah firman Allah. Sedang firman Allah—bagi kalian—qadîm (tak berawal). Maka niscaya hukum Allah—halal dan haramnya—pun qadîm.Kritikan ini lemah dari tiga sisi; pertama, bolehnya bersetubuh dengan perempuan yang dinikahi, dan haramnya dengan perempuan lain (ajnabiyyah), merupakan sifat tindakan hamba. Oleh karena itu dikatakan, ‘setubuh ini halal atau haram’. Tindakan hamba sendiri adalah ‘perkara baru’, dan sifat untuk ‘perkara baru’ tidaklah dikatakan ‘tak berawa’l (qadîm); kedua, dikatakan: perempuan ini halal bagi Zaid ‘setelah’ tidak dihalalkan. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum tersebut adalah ‘baru’; ketiga, konsekuensi dari dihalalkannya setubuh adalah nikah, atau kepemilikan terhadap seorang hamba. Sehingga segala hal yang digantungkan terhadap perkara baru, maka mustahil ‘tak berawal’. Sehingga tetaplah bahwasanya ‘hukum’ tidak mungkin ‘tak berawal’. ‘Firman’ boleh jadi tak berawal, akan tetapi ‘hukum’ bukanlah ‘khitab’."
Selain dalam al-Mahshûl, dalam kitabnya yang lain yang bertajuk Munadzârât, ia mengkritik al-Ghazali dalam perkara tanah ghashab dan mengaitkannya dengan permasalahan teologis yang cukup rumit.Al-Razi kelihatan gerah dengan pengagungan masyarakat Tus, Iran, terhadap al-Ghazali. Ia mengatakan, “kalian menghabiskan umur untuk membaca kitab al-Musthashfâ. Barang siapa mampu menghadirkan argumen dari kitab al-Musthashfâ dan mempresentasikannya di hadapanku tanpa bisa dimasuki argumen lain, maka aku akan memberinya seratus Dinar.” Kemudian datang—sebagaimana penuturan al-Razi—orang yang tercerdas di antara mereka, dan berbicara mengenai shalat di tanah ghashab (al-shalât fî al-ardl al-maghsûbah), sebab ia mengira bahwa perkataan Ghazali dalam permasalahan tersebut sangat kokoh. Menurut al-Ghazali, ‘arah’ shalat dan ghashab terdapat perbedaan yang tak bisa bertemu. Al-Razi membantah,
"shalat terdiri berdiri, duduk, ruku’, sujud. Semua aktivitas ini adalah gerak dan diam. Gerak merupakan aktivitas yang ‘menempati ruang’ setelah sebelumnya ‘berada di ruang lain’. Sedang diam adalah aktivitas berhenti di satu tempat dalam waktu relatif lama. Menempati ruang adalah bagian dari gerak dan diam. Dan keduanya merupakan bagian dari shalat. Jika Anda mengetahui hal ini, maka saya berkata: jika shalat yang berada di tanah ghasab adalah bagian dari penempatan terhadap tanah yang dighashab, maka penempatan ini jelas tidak dibolehkan. Dan bagian dari aktivitas shalat dalam tanah yang dighashab sama juga tidak dibolehkan. Ghashab dan haram di sini menjadi bagian dari aktivitas shalat. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menghubungkan perkara ini dengan shalat. Sebab perintah untuk shalat artinya perintah dengan segala aktivitasnya. Jika aku sudah menunjukkan salah satu aktivitasnya menempati ‘ruang’ tersebut, dan sudah menunjukkan bahwa ‘penempatan’ tersebut tidak diperbolehkan, maka akan ada pertemuan antara perintah dan larangan untuk satu hal dengan satu alasan bersamaan. Dan yang demikian tidak mungkin.
"
Al-Razi juga termasuk sarjana ushul yang menyetujui bahwa rasul bisa berijtihad. Dan ijtihadnya bukan hukum paten yang tidak bisa berubah, seperti dalam strategi perang dan perkara dunia. Lompatan yang cukup signifikan lagi adalah, al-Razi membedakan antara hukum Allah yang paten, dan didasarkan pada teks yang jelas, dengan hukum yang didasarkan pada teks yang masih multi-interpretatif. Untuk yang pertama, tidak bisa dikatakan, “ini adalah Madzhab Fulan”, karena termasuk kategori hukum yang tak bisa ditawar (mâ ulima min al-dîn bi al-dlarûrah). Sedangkan untuk yang kedua (inferensi hukum dari teks yang multi-interpretatif), bisa dikatakan, “ini adalah Madzhab Fulan”. Artinya adalah, fikih dalam perbincangan hukum yang dihasilkan oleh metode yang bermacam dari pelbagai madzhab yang ada sekarang, merupakan “pilihan”.
IV
Teologi Asy’ari sebagai madzhab pemikiran dalam teologi—semenjak kemunculannya pada abad ke 4 H—sangat diperhitungkan dalam dinamika intelektual Arab-Islam. Fakhr al-Din al-Razi adalah salah satu sarjana besar Asy’ari. Ia belajar ilmu kalam pada ayahnya (Dliya' al-Din Umar), kemudian Abi Qasim bin Nashir al-Anshari (w. 511 H), Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 487 H), Abu Ishaq al-Isfrayini (w. 418 H), Abu al-Huseyn al-Bahili, hingga sampai pada Abu al-Hasan al-Asy'ari (w. 234 H). Seperti diungkapkan Ibnu Subki, al-Razi adalah pembaharu keenam—sebagaimana diambil dari hadis Nabi bahwa akan datang pembaharu di setiap seratus tahun—yang datang setelah kurun Imam Ghazali. Bagaimana tidak, jika Asy’ariyyah meletakkan diri di tengah rasionalitas Muktazilah dan literalisme Hanabilah, al-Razi yang merupakan pembesar sekte Asy’ari di abad ke-6, mengikrarkan bahwa akal didahulukan di atas dalil jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Ia mengatakan dalam Asâs al-Taqdîs,
"dalil dalil rasional jika bertentangan dengan teks, bagaimana? Ketahuilah, bahwa jika dalil rasional telah mencapai satu capaian, kemudian argumen teks mengatakan sebaliknya, maka keadaannya tak akan mungkin lepas dari empat hal berikut ini: pertama, rasio akan sesuai dengan teks. Di sini akan ada pembenaran terhadap dua hal yang bertentangan. Dan ini mustahil; kedua, dua-duanya tidak benar. Jelas mustahil pula, karena yang demikian merupakan penolakan terhadap dua hal yang bertentangan; ketiga, yang benar adalah capaian teks, sedangkan capaian rasio tak benar. Ini mustahil juga. Sebab, kita tak mungkin mengetahui kebenaran teks tanpa landasan rasional […..] maka tetaplah (kemungkinan keempat) bahwa tidak menerima rasio untuk membenarkan teks merupakan bentuk penolakan terhadap teks dan rasio bersamaan. Dan ini tak benar. Ketika keempat klasifikasi ini tak bisa diterima, maka yang tersisa tinggal rasio memutuskan bahwa dalil teks adakalanya tidak tepat, atau tepat, akan tetapi yang dimaksud bukan yang tertuang secara tekstual (legitimasi takwil)."
Di sini al-Razi meyakini bahwa dalil rasional independen, sebab mampu membawa teks jauh dari makna literalnya. Artinya, jika terdapat pertentangan, bukan rasio yang kalah. Akan tetapi teks yang kalah. Di titik ini, pengaruh metode Muktazilah terhadap pemikiran al-Razi terlihat lebih kental dari pengaruh sarjana Asy’ariyyah. Akan tetapi jika kita melihat wasiat akhirnya, pada akhirnya al-Razi membuang jauh cara berpikir demikian. Ia mengatakan, "Aku telah menguji beragam metode dalam ilmu kalam, metode-metode filsafat, dan aku tidak melihat manfaat di sana yang bisa menyamai manfaat yang aku temukan di dalam al-Qur’an. Sebab al-Qur’an berusaha untuk menyematkan keagungan dan kebesaran terhadap Allah secara total, dan mencegah untuk tidak terlalu masuk dalam pertentangan dan perdebatan. Hal itu tidak lain karena didasari pengetahuan bahwasanya akal manusia kabur dan terbatas jika dihadapkan pada perkara-perkara sulit nan pelik, dan dihadapkan pada metode yang tidak jelas. Oleh karena itu, aku mengatakan, segala sesuatu yang ditetapkan dengan argumen yang kuat tentang keniscayaan keberadaan-Nya, keesaan-Nya, tidak ada yang serupa dengan eksistensi-Nya yang tak berawal dan tak terikat oleh waktu, pengaturan dan tindakan-Nya—semua ini adalah pendapatku, dan melalui pendapat itu, aku akan (berani) bertemu Allah. Adapun persoalan yang berujung pada kerumitan dan ketidakjelasan, maka semua yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis shahih yang disepakati oleh para imam yang jadi panutan, untuk menunjuk terhadap makna satu, maka hal tersebut akan tetap sebagaimana adanya (tanpa dirubah)."
Jika dikalkulasi, mayoritas karangan al-Razi memang dalam disiplin ilmu kalam. Karangan al-Razi dalam disiplin ini mencapai 34 lebih. Di antaranya adalah Ajwibat al-Masâil al-Najjâriyyah, Asâs al-Taqdîs, Tahshîl al-Haqq, al-Jabar wa al-Qadar, al-Jawhar al-Fard, Hudûts al-Alâm, al-Khalq wa al-Ba’ts, al-Khamsîn fî Ushûl al-Dîn, al-Zubdah fî Ilm al-Kalâm, 'Ishmat al-Anbiyâ’, Nihâyat al-‘Uqûl fî Dirasât al-Ushûl, al-Arba’în fî Ushûl al-Dîn, al-Bayân wa al-Burhân, Irsyâd al-Nudzdzâr ilâ Lathâif al-Asrâr, Tahshîl al-Haq, al-Risâlah al-Kamâliyyah fi al-Haqâiq al-Ilâhiyyah, al-Mahshûl fî Ilm al-Kalâm, Ma’alim Ushûl al-Din, Syarh Asmâ Allâh al-Husnâ, I’tiqadât Firaq al-Muslimîn wa al-Musyrikîn, al-Isyârah fî Ilm al-Kalâm. Sedang karangan al-Razi yang memuat dua disiplin bersamaan (kalam dan filsafat) adalah: Muhashshal Afkâr al-Mutaqaddimîn wa al-Muta’akhkhirîn min al-Ulâma’ wa al-Hukâma wa al-Mutakallimîn dan al-Mathâlib al-Âliyah.
Dalam disiplin ini, ada dua karya al-Razi yang akan sedikit penulis jabarkan lebih lanjut. Pertama adalah Al-Isyârah fî Ilm al-Kalâm. Kitab ini terkadang ditulis dengan redaksi Tanbîh al-Isyârat, atau al-Isyârât. Seperti ditutukan Abdul Wahhab al-Mushili, al-Razi mengarang al-Isyârah setelah ia mengarang al-Arba’în. Dan al-Isyârâh juga dikarang setelah al-Razi mengarang I’tiqâdât dan Risâlat al-Ma’âd. Al-Isyârah merupakan kitab yang secara spesifik mendeskripsikan pemikiran Asy’ariyyah. Yang menjadikan buku ini menarik adalah, al-Razi di kitabnya ini, tidak mempergunakan redaksi yang susah sebagaimana di kitab lainnya, seperti dalam Nihâyat al-Uqûl, atau al-Mathâlib al-‘âliyah, dan ketika mendiskusikan argumen lawan, al-Razi mencukupkan dengan redaksi yang cukup ringkas. Hal ini yang menjadikan kitab ini diberi judul: al-Isyârah, maksudnya hanya menunjukkan dengan ringkas argumen lawan. Walaupun buku ini dikarang bukan di awal kesibukannya mengarang kitab, akan tetapi substansi kitab ini lebih mirip pengantar memasuki ilmu kalam. Substansi buku ini faktanya hanya mengulang substansi al-Arbaîn.
Seperti dikatakan di atas, mayoritas buku ini merepresentasikan al-Razi sebagai sarjana Asy’ari. Dalam permasalahan yang Asy’ariyyah sendiri terdapat perbedaan, al-Razi dengan tegas mengamini satu tokoh jika sesuai nalar pikirnya. Seperti ia mengamini Asy’ari ketika menjabarkan ilmu ‘tidak niscaya’ terlahir dari penelitian (al-nadzar), akan tetapi tetap melalui ‘campur tangan Tuhan’—sembari mengutarakan penolakan terhadap pandangan yang menyatakan bahwa penelitian menghasilkan pengetahuan, ‘niscaya’ membuahkan pengetahuan, dan selalu melekat dengan penelitian. Sebab, segala sesuatu yang mungkin terjadi (mumkinât) di dunia ini, disandarkan pada kekuasaan Allah. Segala hal yang sama-sama ‘baru-diciptakan’, tidak berelasi dengan hal ‘baru’ lainnya terkecuali hanya pada batas ‘kebiasaan’. Sebagaimana api yang ‘biasa’—bukan niscaya—membakar. Artinya, relasi antara api-membakar atau penelitian-ilmu, bukanlah relasi yang niscaya. Ia menyatakan,
"argumentasinya adalah, jika penelitian menjadi sebab bagi ilmu, atau melekat, niscaya penelitian tak akan mendahului pengetahuan, karena tak mungkin sesuatu dihasilkan, melekat dan disebabkan oleh ketiadaan. Sebagaimana ketika jawhar (substansi), jika melekat dengan ‘ardl (makna yang melekat pada jawhar), maka salah satu dari keduanya tak mungkin mendahului yang lain. Sedang di sini tak mungkin ada penelitian ketika pengetahuan sudah ada. Maka jelaslah bahwa keduanya tak berelasi. Dan pengetahuan dihasilkan berdasarkan kebiasaan."
Sebagai seorang Asy’arian, al-Razi mengkritik Hanabilah yang memandang bahwa ilmu kalam tak boleh dipelajari dan memandang Allah serupa dengan tubuh (corpus/jism). Sebagaimana al-Razi mengkritik para filsuf pada—misalnya—permasalahan jism dan spesifikasi pengetahuan Allah. Baginya, jism mempunyai awal-tercipta (muhdats)—sedang di satu sisi para filsuf berpandangan bahwa jism tak berawal. Ia pun mengkritik pandangan filsuf dan Muktazilah yang menyatakan bahwa Allah tak bisa dilihat. Walaupun Al-Razi menyepakati beberapa tokoh Muktazilah; Abu Hudzail al-Allaf, Abu Qasim al-Bulkhi, Abu Husayn al-Bahsri, dalam permasalahan ‘ketiadaan’ tidaklah menunjukkan apapun. Bahkan dalam beberapa permasalahan, ia mengkritik al-Baqilani karena dianggap tidak berjalan dalam bingkai pemikiran Asy’ariah. Yang menunjukkan bahwa al-Razi mengamini pandangan-pandangan Asy’ari, ia menyebut madzhab ini dengan Madzhab Ahl al-Haqq. Dan al-Razi menyebut Imam Asy'ari dengan Syaikhunâ.
Buku al-Razi lainnya yang menarik dikaji adalah Muhashshal Afkâr al-Mutaqaddimîn wa al-Muta’akhkhirîn. Karya ini tetap dikaji hingga di dua kurun setelah kurun al-Razi. Hal itu disebabkan, Muhashshal merupakan representasi pemikiran sarjana Asy’ari era akhir. Dalam Muhashshal sendiri tidak disebutkan kapan dan di mana al-Razi mengarang kitab ini. Tetapi menurut Uraybi, melihat kitabnya yang lain, Syarh al-Isyârât dan Nihâyat al-Uqûl, kita bisa memperkirakankapan al-Razi mengarang kitabnya tersebut. Dua kitab ini dikarang oleh al-Razi sebelum tahun 582 H, sebelum ia berkelana ke Transoxania. Menurut penuturan al-Razi secara implisit di Muhashshal, ia mengarang buku-buku teologi, logika, dan filsafat sebelum al-Razi mengarang Muhashshal. Sebagaimana disebutkan juga dalam pembukaan bukunya, alasan al-Razi menulis buku ini adalah beberapa orang penting memintanya untuk meringkas pendapat para imam terdahulu, baik itu filsuf maupun teolog, di mana pembahasannya lebih menitikberatkan pada permasalahan fundamental.
Dalam Muhashshal, di satu sisi, al-Razi mengkritik filsafat sebagai sebuah madzhab, pun tokoh-tokohnya, semisal Aristoteles dan Ibnu Sina di sisi yang lain. Begitu pula ia mengkritik Asy’ariyyah sebagai sebuah sekte di satu sisi, pun mengkritik para sarjananya, semisal Asy’ari, al-Baqilani dan al-Juwayni di sisi yang lain. Atau Muktazilah sebagai sebuah sekte, dan tokohnya semisal Abdul Jabbar dan al-Jubbai. Akan tetapi tak jarang al-Razi menyatakan kesepakatannya dengan mereka dalam satu permasalahan. Hal ini menunjukkan, al-Razi tak fanatik terhadap satu madzhab pemikiran. Akan tetapi ia mencoba memilah permasalahan-permasalahan dengan cermat, serta tak terburu-buru menyematkan sebuah pendapat terhadap satu sekte, jika kenyataannya pendapat tersebut hanya diimani oleh satu tokoh dalam sekte tersebut.
Sebagai sampel, kita bisa melihat saat al-Razi mengkritik pemikiran Abu al-Hasan al-Asy’ari, dan pengikutnya dengan penyebutan yang seolah menyiratkan bahwa ia bukan bagian dari kelompok tersebut. Ia mengatakan, "Abu al-Hasan al-Asy’ari dan pengikutnya berpendapat bahwasanya Tuhan kekal melalui sifat di luar Dzat, sedang al-Qadli al-Baqilani dan Imam Haramayn meyakini sebaliknya—dan pendapat inilah yang benar." Al-Razi juga mengatakan, "Abu al-Hasan al-Asy'ari memandang bahwa kuasa hamba tidak bisa mempengaruhi perbuatannya. Akan tetapi yang memberikan pengaruh adalah kuasa Allah."
Muhashshal mengarah pada capaian yang cukup signifikan dalam fase pemikiran al-Razi: al-Razi mengimani bahwa filsafat dan antar madzhab dalam teologi tak mutlak sepenuhnya bertentangan. Akan tetapi di satu permasalahan ada kesesuaian di antara keduanya yang tak harus diperuncing. Tentu saja, sebab Al-Razi dikenal sebagai sosok yang ‘berani’ menggambungkan ilmu kalam dan filsafat. Ilmu yang terlahir dari keduanya—dalam perspektif al-Razi—itu disebut dengan al-Ilm al-Ilâhi (ilmu ketuhanan). Al-Razi termasuk sarjana Asy’ari era akhir yang mengawali memasukkan pembahasan filsafat dalam ilmu kalam. Ignaz Goldziher sebagaimana dikutip Shalih al-Zirkan, pun menyatakan bahwa al-Razi merupakan sarjana yang mengamini kaidah-kaidah ilmu kalam—yang dalam perkembangannya—lebih banyak mengacu pada filsafat Aristoteles sebagai neraca pemikiran. Langkah ini, sebagaimana menimbulkan resistensi—semisal dari al-Sanusi dengan Umm al-Barâhîn, juga memunculkan apresiasi—sebagaimana dari Sa’d al-Din al-Taftazani dengan al-Maqâshid. Bagi yang mengapresiasi ‘harmonisasi’ filsafat dan ilmu kalam, mereka meyakini bahwa metode filsafat akan semakin menguatkan nilai-nilai fundamental akidah dan meluaskan ruang pikir.
Perbedaan mendasar para teolog awal dengan teolog era akhir dalam penggabungan antara filsafat dan kalam adalah, teolog era akhir lebih ‘ndaqiq’ dalam permasalahan filsafat, hingga seakan-akan hendak membuang ilmu kalam. Oleh karena itu, kitab kalam di era belakang, justru lebih mirip dengan buku filsafat, sebagaimana dalam buku al-Mawâqif. Dalam arti, kitab teolog di era akhir memang tidak seperti kitab kalam yang memuat pandangan filsafat—sebagaimana pandangan Ibnu Khaldun, akan tetapi lebih mirip benar-benar buku filsafat. Mungkin hal ini yang menjadikan al-Razi—oleh beberapa ulama—lebih akrab disapa ‘filsuf’ dari pada ‘teolog’. Sebagaimana banyak juga yang tetap kokoh mempertahankan al-Razi sebagai teolog. Pada tahap ini pemikiran al-Razi dalam teologi terkesan bertentangan. Maka, untuk memahami pemikiran al-Razi, kita pun harus memahami fase pemikirannya. Ada baiknya kita simak tesis Mahmud Qasim yang telah berjasa memetakan fase pemikiran sosok besar ini. Menurut Mahmud Qasim, al-Razi di awal ‘karirnya’ adalah seorang teolog, kemudian filsuf, selanjutnya ia lebih memilih 'berdiam' (tawaqquf), kemudian kembali sebagai seorang teolog yang menggambungkan beragam metode filsafat dengan ilmu kalam. Oleh Shalih al-Zirkan, tesis Mahmud Qasim diaplikasikan terhadap pemilahan buku al-Razi; pertama, buku filsafat murni, seperti al-Mabâhits al-Masyriqiyyah, al-Mulakhkhas fi al-Hikmah wa al-Mantiq, Syarh al-Isyârât wa al-Tanbihât, dan Uyûn al-Hikmah; kedua, buku teologi, seperti al-Isyârah, al-Arbaîn, Nihâyat al-Uqûl dan al-Ma’âlim fu Ushûl al-Dîn; ketiga, percampuran antara metode filsafat dan kalam, seperti Muhashshal dan al-Mathâlib al-Âliyah; keempat, buku yang berusaha merasionalkan al-Qur’an, membahas akidah dari sudut pandang ayat al-Qur’an, atau hendak kembali pada metode al-Qur’an, seperti dalam al-Tafsir al-Kabîr.
V
Kepakaran dan kemasyhuran al-Razi dalam ilmu kalam hampir menyamai kepakaran al-Razi dalam tafsir. Dalam disiplin tafsir, al-Razi mempunyai kitab legendaris dan fenomenal yang diberi judul Mafâtih al-Ghayb atau al-Tafsîr al-Kabîr. Buku al-Razi –yang menurut Thasy Kubri Zadah dianggit setelah ia menjadi seorang sufi—telah menyita banyak perhatian dari peneliti, hingga pada satu masa—menurut al-Dzahabi—tidak ada kitab tafsir yang dikaji lagi selain Mafâtîh al-Ghayb ini. Ibnu Taymiah tatkala mengomentari tafsir ini mengatakan, "di dalamnya ada segala hal, terkecuali tafsir." Akan tetapi yang disampaikan Ibnu Taymiah dibantah oleh al-Subky dengan mengatakan, "bukan seperti itu. Akan tetapi, bersama tafsir, terdapat segala hal." Selain itu, al-Razi juga mempunyai kitab lain dalam disiplin tafsir, di antaranya adalah Ahkâm al-Basmallah, Asrâr al-Tanzîl wa Anwâr al-Ta’wîl atau kerap disebut Tafsîr al-Qur’an al-Shaghîr, al-Burhân fî Qira’at al-Qur’an, Mafâtîh al-Ulûm atau Tafsîr Surat al-Fâtihah, Tafsîr Surat al-Baqarah ‘alâ Wajh al-Aqliy lâ al-Naqliy, Tafsîr Surat al-Ikhlâsh, Risâlah fî Ma’ânî al-Mutasyâbihât, dan Rûh al-‘Ajâib.
Terkait al-Tafsîr al-Kabîr, Thaha Jabir al-Ulwani merangkum tiga pandangan sarjana kontemporer dalam menilai kesahehan penisbatan buku ini: Pertama, para sarjana yang menganggap tafsir ini bukan karangan al-Razi. Akan tetapi karangan salah seorang muridnya. Argumennya diambil dalam tafsiran surat al-Wâqi’ah yang berbunyi, "permasalahan ini saya lihat dari perkataan al-Razi setelah saya menyelesaikan tulisan ini." Menanggapi pernyataan itu, komentator dari percetakan al-Bahiyyah al-Mishriyyah itu mengatakan, "pernyataan ini menyiratkan, dan menguatkan bahwa kitab tersebut bukan karangan al-Razi, akan tetapi karangan salah satu muridnya, bahkan mungkin juga dari ulama era akhir." Menurut Thaha Jabir, ungkapan tersebut merupakan ungkapan tergesa-gesa. Karena teks tafsir dari awal hingga surat Wâqi'ah jelas mengindikasikan bahwa tafsir tersebut merupakan karangan al-Razi. Dan semua sejarawan sepakat, al-Razi mengarang kitab tafsir yang diberi nama Mafâtîh al-Ghayb. Kedua, sarjana yang menganggap al-Razi tidak menyelesaikan kitabnya itu. Najmuddin Ahmad bin Muhammad al-Qumuly lah (w. 727 H) yang merampungkan kitab itu, dan Syihab al-Din bin Khalil al-Khuby al-Dimasyqi (w. 639 H) menyempurnakan yang kurang. Di antara yang meyakini pendapat ini adalah Abdurrahman al-Mu’allimi dan Muhammad Husayn al-Dzahabi. Adapun Muhammad Ali al-Immary meyakini bahwa surat al-Wâqi’ah memang tidak dikarang oleh al-Razi. Selain surat Wâqi’ah, ia tetap meyakini bahwa kitab itu merupakan karangan al-Razi.
Adapun pandangan ketiga, para sarjana yang meyakini bahwa al-Razi merampungkan kitabnya itu. Mereka mentakwil pernyataan dalam buku sejarah dan tafsir terkait yang mengindikasikan al-Razi tidak merampungkan Mafâtîh al-Ghayb. Di antaranya adalah Ibnu Asyur, Shalih al-Zirkan, Muhsin Abdul Hamid. Akan tetapi terkadang pentakwilan mereka terkesan berlebihan, walaupun beberapa ada yang masuk akal. Menurut Thaha Jabir al-Ulwani, al-Razi memang menyelesaikan tafsir ini sepenuhnya. Akan tetapi, naskah yang dicetak adakalanya memang diambil dari tulisan al-Razi yang sudah diedit, dan adakalanya diambil dari tulisan yang didiktekan oleh al-Razi, hingga terdapat beberapa editing dan tambahan yang tak dicocokkan dengan naskah aslinya.
Dalam al-Tafsîr al-Kabîr, al-Razi memasukkan permasalahan-permasalahan yang cukup asing jika dikaitkan dengan disiplin tafsir. Ia beralasan, al-Qur’an merupakan kitab suci yang merangkum semua ilmu. Tak heran jika surat al-Fatihah di tangan al-Razi dijabarkan hingga mendekati tiga ratus halaman. Ia mengatakan di awal tafsirnya, "saya sudah mengatakan dalam beberapa kesempatan, bahwa dari surat ini mampu ditafsirkan sepuluh ribu permasalahan. Akan tetapi orang-orang yang bodoh tidak mempercayainya. Dan mereka mengomentari surat al-Qur’an ini dalam buku-bukunya dengan komentar kosong tanpa arti, dan kalimat yang tidak bisa memberikan substansi. Ketika aku menganggit kitab ini, aku mengajukan kata pengantar ini sebagai pengingat bahwa apa yang sudah aku sampaikan sesuatu yang bisa dan dekat kemungkinan terjadi."
Apa yang disampaikan al-Razi ini bisa dilihat saat ia menafsirkan ayat-ayat dalam bukunya itu. Oleh karena itu, saat menafsirkan ayat, ia menjelaskan korelasinya dengan ayat sebelum dan setelahnya, kemudian menjabarkan kandungan ayat, serta disiplin ilmu lain yang berkorelasi dengan ayat, seperti matematika, naturalisme, astronomi, entah itu menyandarkan pada perkataan ulama dalam disiplin ilmu tersebut, atau malah meruntuhkan argumennya. Al-Razi sangat jarang menafsirkan sebuah ayat—tentang Nabi, atau raja dan umat terdahulu—dengan cerita-cerita yang dikutip oleh beberapa penafsir dari para sejarawan, terkecuali jika memang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Ia menganggap, penafsir tidak cukup hanya dengan mengutip sebuah pendapat tentang ayat dari para ulama klasik saja, akan tetapi harus mentarjih dan memilih, serta menjelaskan yang salah dan yang benar dengan argumen yang ditopang dari syariat dan bahasa.
Inklinasi teologis jelas terlihat dalam buku tafsirnya ini. Setiap ada ayat yang berkenaan dengan ilmu kalam, al-Razi sangat terlihat ‘antusias’ untuk membahasnya secara terperinci. Sebagai misal dalam penafsirannya terhadap ayat, “sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa sesuatu yang berguna bagi manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi setelah sebelumnya gersang (mati), dan Dia sebarkan di bumi segala jenis hewan, pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” kita bisa melihat al-Razi mengklasifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ayat ini. Ia mengatakan,
"permasalahan pertama, ayat ini mengindikasikan bahwa ‘proses mencipta’ (al-khalq/al-takwîn) adalah ‘makhluk’. Karena Allah mengatakan, ‘sesungguhnya penciptaan langit dan bumi[…..]sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’, sangat jelas, bahwa ayat ini berbicara tentang makhluk. Karena makhluk adalah yang menunjukkan terhadap Pencipta. Maka teranglah bahwa ‘proses mencipta’ adalah ‘makhluk’."
Sesungguhnya pada permasalahan ini terdapat perbedaan antara Asy’ariah dengan Maturidiyyah. Asy’ariyyah—termasuk al-Razi—berpendapat bahwa ‘proses mencipta’ adalah ‘makhluk’, sedang Maturidiyyah berpendapat ‘proses mencipta’ bukanlah ‘makhluk’. Maturidiyyah berpendapat bahwa ‘proses mencipta’ termasuk sifat yang ada dengan sendirinya (shifat al-ma’ânî), tak berawal, dan berhubungan dengan proses ‘pengadaan’ makhluk dan mengeluarkannya dari ‘ketiadaan’ hingga terbentuk menjadi ‘ada’. Sedang menurut Asy’ariyyah, sifat yang berhubungan dengan proses ‘pengadaan’ dari ketiadaan bukanlah ‘proses mencipta’ (al-khalq/al-takwîn), akan tetapi kuasa (al-qudrah). Kuasa Allah sendiri dari sudut pandang relasi ada dua: kuasa Allah akan pengadaan makhluk, dan realisasi pengadaan itu sendiri. Jika yang pertama ‘tak berawal’, maka yang kedua ‘berawal’, karena berelasi dengan makhluk. Dengan kata lain, ‘proses mencipta’ adalah berkaitan realisasi ‘pengadaan’ itu sendiri yang berkaitan dengan makhluk. Sebab, jika ‘proses mencipta’ adalah nisbat yang tidak bisa diperkirakan terkecuali melalui wujud objek, maka jika objek ‘berawal’, dengan sendirinya ‘proses’ itupun harus ‘berawal’.Al-Razi melanjutkan,
"permasalahan kedua, berkata Abu Muslim: kata ‘al-khalq’ di dalam lisan orang Arab mempunyai makna ‘memperkirakan’, kemudian menjadi nama bagi perbuatan Allah. Sebab semua perbuataan-Nya pasti benar[…] permasalahan ketiga, kewajiban membuktikan adanya Pencipta dengan dalil rasional, dan buruknya pendasaran pengetahuan itu pada taklid, permasalahan keempat, Ibnu Jarir menuturkan dalam sebab turunnya ayat, dari Atha’, tatkala Nabi sampai di Madinah, turun ayat ‘dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu’, kemudian Kafir Quraisy berkata, ‘bagaimana Tuhan ada satu sedang manusia banyak’. Turunlah ayat ini."
Ia melanjutkan membahas delapan hal yang disebutkan dalam ayat kemudian, memerincinya secara detail dan tak segan ia membahas ilmu astronomi sampai berlembar-lembar untuk sekedar menguatkan tesisnya. Misalnya, dalam membahas ‘langit’, al-Razi membagi empat belas permasalahan untuk membuktikan wujud Pencipta. Al-Razi mengutip pendapat Ptolemy, dan para astronom kuno dari Babilonia, Cina, Mesir, Romawi dan Syam, serta terkadang mengkritiknya. Semuanya kembali pada tesis, bahwa bintang-bintang, yang secara natural mempunyai ukuran tertentu, mempunyai ruang tertentu, dan bergerak ke arah tertentu, semua menunjukkan di luar sana ada Pengatur yang mengatur ini semua.
Bahasa juga salah satu objek yang cukup serius dibahas dalam tafsir ini. Misal, tatkala al-Razi menafsirkan kalimat, “bismil-Lâh al-rahmân al-rahîm”. Ia mengatakan bahwa huruf “ba” dalam kalimat tersebut, berhubungan dengan kata yang tersimpan (mudlmar). Yang tersimpan ini adakalanya kata benda atau kata kerja, baik itu di awal atau di akhir. Jika yang tersimpan adalah kata benda yang di awal, sebagaimana perkataan: ibtidâ’ al-kalâm bi ismil-Lah. Jika yang tersimpan adalah kata kerja di awal, seperti: abda’ bi ismil-Lah. Dan jika yang tersimpan adalah kata benda yang di akhir, misalnya: bi ismil-Lah ibtidâ’î. Sedang jika kata kerja di akhir adalah 'bi ismil-Lah abda’. Al-Razi juga mempertanyakan, manakah yang lebih baik, mendahulukan ataukah mengakhirkan? Menurutnya, keduanya ada di dalam al-Qur’an. Argumen ‘di awal’ seperti dalam Firman Allah, “bismil-Lah majrâhâ wa mursâhâ”, sedang ‘di akhir’, seperti dalam firman, “iqra’ bi ismi rabbik”. Akan tetapi al-Razi kemudian lebih menguatkan pendapat yang di awal dengan argumen dari al-Qur’an dan logika bersamaan. Dari al-Qur’an seperti dalam firman, iyyâka na’bud. Di sini kata kerja benda ada di awal. Maka dalam lafadz “bi ism” juga harus demikian. Sedang secara logika, karena Allah tak berawal, dan ‘ada’ dengan tidak membutuhkan pada siapapun dan apapun. Oleh karean itu wujudnya harus mendahului wujud yang lain. Yang dahulu wujudnya lebih utama untuk disebutkan. Maka, bismil-Lah abtadi’ lebih utama.
Begitu juga permasalahan fikih, seperti penulis sudah singgung di atas. Dan tentu saja ilmu al-qur’an dan ushul fikih. Ushul fikih dan fikih umumnya menempati porsi yang cukup dominan pada saat berkenaan dengan ayat-ayat hukum. Secara garis besar, dalam pembahasan setiap disiplin ilmu dalam kitab ini, rasionalitas al-Razi sangat dominan. Sedang kepakaran al-Razi dalam ilmu hadis, kitab tafsir ini oleh sebagian kalangan dianggap merepresentasikan kepakaran al-Razi dalam ilmu hadis—walaupun ia tak diperhitungkan dalam disiplin ini. Al-Razi, dalam ayat hukum, kerap melegitimasi ‘keputusannya’ dan menguatkannya dengan hadis-hadis Nabi.
VI
Spirit pembaharuan dalam pemikiran al-Razi bisa dilihat dari terobosan-terobosan yang ia lakukan. Dalam disiplin kalam, sebagai misal, bagaimana ia mengharmoniskan filsafat dan ilmu kalam sebagai sebuah metode baru yang dinamakan 'ilmu ketuhanan'. Ia pun dengan tegas mengikrarkan bahwa rasio harus didahulukan jika bertentangan dengan teks. Dalam disiplin tafsir, terlihat dari lompatan al-Razi yang menganggap kreasi-kreasi dalam memahami ayat-ayat Tuhan harus tetap dilakukan. Sedang fikih dimodifikasi di tangannya menjadi ilmu rasional dengan tidak mengabaikan teks sebagai neraca berpikir. Maka tak heran ketika Ibnu al-Subki menyebut al-Razi sebagai pembaharu abad ke-6, setelah Abu Hamid al-Ghazali. Rasionalisme al-Razi tentu saja membuat gerah sarjana yang tak berkutik dengan argumennya, semisal, al-Syahrazuri, al-Dzahabi, Ibnu Taymiah, dan Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Khuwansari, Abu Syamah al-Maqdisi, dan lain sebagainya.
Tatkala sakit, ia mendiktekan surat wasiat pada muridnya, Ibnu Abi Bakr al-Asfhihani pada tahun 606 H. Di surat wasiatnya itu, ia meminta perihal kewafatannya tak diberitahukan ke orang lain. Sebab, al-Razi khawatir terhadap musuhnya, Muktazilah, Hasyawiyyah, Syi'ah, Karamiyyah, akan terus mengincar walaupun pada saat ia sudah meninggal. Tak diketahui apakah wasiat al-Razi dilaksanakan oleh para murid dan pengikutnya, ataukah mereka mengabaikannya. Yang jelas, sampai sekarang tak bisa dipastikan—dan terdapat perbedaan di kalangan sejarawan-- di mana al-Razi pada akhirnya dimakamkan. Al-Razi meninggal di tahun ia berwasiat, 606 H. Berikut adalah wasiat lengkap al-Razi, sebagaimana dituliskanThaha Jabir al-Ulwani yang dikutip dari berbagai sumber,
Seseorang yang mengharapkan rahmat Tuhannya, dan mempercayai kemuliaan kekasihnya, Muhammad bin Umar bin al-Husayn al-Razi--pada saat saat terakhirnya di dunia, dan permulaan di akhirat; waktu di mana orang yang keras sekalipun menjadi lunak, dan orang yang hendak lari harus menghadap Tuhannya--mengatakan:
Aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang diucapkan oleh pembesar Malaikat-Nya di waktu utama mereka menghadap Tuhan, dan diucapkan oleh pembesar nabi-Nya di pilihan waktu tersingkap tabir mereka, bahkan aku mengucapkannya sebab konsekuensi seorang makhluk. Oleh karena itu aku memujinya dengan pujian-pujian yang sifat ketuhanan-Nya berhak menerimanya, pun kesempurnaan sifat murah-Nya meniscayakan pujian itu, baik yang aku tahu, ataupun aku tak mengetahuinya, sebab tidak bisa disamakan antara debu (manusia), dengan keagungan Tuan segala tuan.
Salam hormatku terhadap Malaikat yang diberi keistimewaan derajat kedekatan dengan Tuhan, beserta nabi-nabi yang diutus, dan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh.
Selepas ini, aku berkata: ketahuilah saudaraku seagama, dan saudaraku pencari kebenaran, bahwa orang-orang mengatakan, “jika seseorang meninggal maka relasinya akan terputus dengan hamba,” keumuman kalimat ini mengecualikan dua hal: pertama, bahwasanya masih tersisa perbuatan baik yang menjadi sebab bagi doa. Dan doa mempunyai dampak tersendiri di samping Tuhan; kedua, hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan anak-anak, cela serta pengembalian hak-hak orang lain dan hak-hak yang dilanggar sebab aniaya (menjadikan orang yang meninggal masih senantiasa berhubungan dengan hamba).
Adapun yang pertama, ketahuilah bahwa aku adalah laki-laki yang mencintai ilmu, oleh karena itu aku menulis tulisan dalam semua disiplin, dengan tidak dibatasi oleh kuantitas dan ideologi tertentu; entah itu dalam perkara benar ataupun tidak benar, buruk ataupun baik. Hanya saja, yang aku lihat dalam buku-buku yang bagiku muktabar: alam yang bisa diindera ini berada dibawah kuasa Penguasa—di mana Penguasa tersebut terbebas dari perumpamaan benda yang menempati ruang dan sifat yang tidak tetap, serta tersifati dengan kesempurnaan kuasa, ilmu dan rahmat.
Aku telah menguji beragam metode dalam ilmu kalam, metode-metode filsafat, dan aku tidak melihat manfaat di sana yang bisa menyamai manfaat yang aku temukan di dalam al-Qur’an. Sebab al-Qur’an berusaha untuk menyematkan keagungan dan kebesaran terhadap Allah secara total, dan mencegah untuk tidak terlalu masuk dalam pertentangan dan perdebatan. Hal itu tidak lain karena didasari pengetahuan bahwasanya akal manusia kabur dan terbatas jika dihadapkan pada perkara-perkara sulit nan pelik, dan dihadapkan pada metode yang tidak jelas.
Oleh karena itu, aku mengatakan, segala sesuatu yang ditetapkan dengan argumen yang kuat tentang keniscayaan keberadaan-Nya, keesaan-Nya, tidak ada yang serupa dengan eksistensi-Nya yang tak berawal dan tak terikat oleh waktu, pengaturan dan tindakan-Nya—semua ini adalah pendapatku, dan melalui pendapat itu, aku akan (berani) bertemu Allah.
Adapun persoalan yang berujung pada kerumitan dan ketidakjelasan, maka semua yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis shahih yang disepakati oleh para imam yang jadi panutan untuk menunjuk terhadap makna satu, maka hal tersebut akan tetap sebagaimana adanya (tanpa dirubah). Adapun yang tidak seperti itu, aku menyatakan:
Hai Tuhan semesta alam, aku melihat semua makhluk sepakat bahwa Engkau adalah Dzat yang Termulia, Pemurah; apa yang sudah aku tuliskan dengan penaku, atau yang terbesit dalam pikiran, maka aku mempersaksikan pengetahuan-Mu. Dan aku mengatakan: jika Engkau mengetahui bahwasanya aku memenangkan ketidakbenaran, atau merobohkan kebenaran, maka lakukanlah sepantasnya padaku. Adapun jika Engkau mengetahui bahwa aku berusaha menguatkan apa yang aku yakini sebagai sebuah kebenaran, melalui pemahamanku bahwasanya itu benar, maka semoga rahmat-Mu dengan tujuanku, bukan hasilku. Hal itu adalah kesungguhan pencarian. Engkah adalah Dzat paling pemaaf, kalau hanya untuk sekedar mempersulit orang yang bersalah. Maka selamatkanlah aku, kasihanilah aku, tutuplah kesalahanku, hilangkanlah kesukaranku, Hai Dzat yang tidak bertambah kekuasaanMu dengan bertambahnya orang-orang yang bertakwa, dan tidak berkurang dengan kesalahan orang yang bersalah.
Aku mengatakan: agamaku mengikuti Muhammad Saw., dan kitabku adalah al-Qur’an yang agung, dan pada keduanya aku bersandar dalam pencarian agamaku.
Hai Dzat pendengar suara, pengabul doa, pemaaf kesalahan, pengasih kesedihan, pengendali alam, aku benar-benar berbaik sangka pada-Mu; luas harapanku terhadap rahmat-Mu, sedang Engkau pernah mengatakan, “Aku berdasar persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku,” dan Engkau mengatakan, “siapa yang memperkenankan orang dalam kesulitan apabila berdoa kepada-Nya?”, dan Engkau mengatakan, “jika hamba-hambaKu bertanya padamu tentang-Ku, maka jawablah bahwasanya Aku dekat”. Taruhlah, aku datang tidak membawa apapun, maka Engkau adalah Dzat Kaya lagi Mulia, dan aku adalah orang yang butuh serta berdosa.
Aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan bagiku selain Engkau, tidak ada Dzat yang baik selain Engkau. Aku mengakui bahwa aku tergelincir, kurang, tidak sempurna, lemah, maka jangan sia-siakan harapanku, dan jangan Engkau tolak doaku. Jadikanlah aku terlindungi dari siksa-Mu sebelum meninggal, atau ketika meninggal dan setelah meninggal. Mudahkanlah untukku sakarat al-mawt, ringankanlah kematian untukku, dan jangan persulit aku dengan siksa dan sakit, karena Engkau adalah Dzat yang Maha Pengasih.
Adapun buku-buku ilmiah yang aku tulis, atau ketika aku terlalu banyak melempar persoalan terhadap orang-orang terdahulu, maka untuk yang memperhatikannya, jika melihat ada kebaikan di sana, sertakanlah aku di setiap doa sebagai hadiah dan nikmat. Adapun jika melihat kejelekan di sana, maka hapuslah perkataan yang tidak pantas. Tidak lain aku hanya ingin memperbanyak diskusi dan mengasah pikiran. Dan semuanya tetap bergantung pada Allah.
Hal penting kedua, memperbaiki keadaan anak-anak beserta cela (ku). Aku menggantungkan semua ini pada Allah kemudian pada pengganti-Nya, Muhammad (sulthan Muhammad ‘Ala al-Din)—semoga Allah menjadikannya setingkat derajat kakaknya dalam agama dan keluhuran, Muhammad. Hanya saja sulthan yang agung tidak bisa mengurus perkara anak-anak, maka aku berpandangan, seharusnya menyerahkan urusan anak-anakku pada Fulan. Dan aku meminta agar ia senantiasa bertakwa pada Allah: “bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik”.
Ibnu Abi Ushaybi’ah mengatakan, “ia berwasiat sampai tuntas.” Kemudian berkata, “aku mewasiatkan, aku mewasiatkan, kemudian aku mewasiatkan: untuk benar-benar mendidik anakku, Abu Bakar. Tanda-tanda kecerdasan dan kepintaran tampak jelas di dirinya. Semoga Allah membuatnya sampai pada kebaikan.”
Aku memerintahkan pada Fulan, dan pada semua murid-muridku, dan orang-orang yang aku mempunyai hak terhadapnya: jika aku meninggal, untuk benar-benar menyembunyikan kematianku, dan tidak memberitahu siapapun mengenai hal ini; mengkafaniku dan menguburkanku dengan tata cara islami, kemudian membawaku ke gunung dekat desa Mizdaqan dan menguburkanku di sana. Jika meletakkanku di liang lahat, maka bacakanlah semampunya untukku ayat-ayat al-Qur’an tentang ketuhanan, kemudian tutuplah aku dengan debu. Selepas itu, katakan, “Hai Dzat yang Mulia, orang yang fakir lagi membutuhkan datang pada-Mu, maka berbaik hatilah padanya.”
Ini adalah akhir wasiatku pada tulisan ini. Allah adalah Dzat yang bebas berbuat atas apa yang Dia kehendaki. Dan untuk apa yang dikehendaki, Allah pasti kuasa akan hal itu. Untuk berbuat baik, Allah teramat pantas untuk itu.
Daftar Pustaka
Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Huseyn (1986). Asâs al-Taqdîs. Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah
Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Huseyn (tt). Muhashshal Afkâr al-Mutaqaddimîn wa al-Muta'akhkhirîn min al-Ulamâ' wa al-Hukamâ' wa al-Mutakallimîn. Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah
Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Huseyn (2007). Al-Isyârah fî Ilm al-Kalâm. Jordan: Markaz Nur al-Ulum li al-Buhuts wa al-Dirasat
Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Huseyn (tt). Manâqib al-Imâm al-Syâfi'i. Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah
Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Huseyn (1988). Al-Mahshûl fî Ilm Ushûl al-Fiqh. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Huseyn (1996). Munadzârât al-Râzi fi Bilâdi Mâ warâ’a al-Nahr. Beirut: Muassasah Izz al-Din
Al-Zirkan, Muhammad Shaleh (tt). Fakhr al-Dîn al-Râzî wa Arâuhu al-Kalâmiyyah wa al-Falsafiyyah. Dar al-Fikr.
Khalif, Fathullah (1976). Fakhr al-Dîn al-Râzi. Kairo: Dar al-Jami'at al-Mishriyyah
Al-Uraybi, Muhammad (1996). Al-Munthalaqat al-Fikriyyah indâ al-Imâm al-Râzi. Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani
Al-Ulwani, Thaha Jabir (2010). Al-Imâm Fakhr al-Dîn al-Râzi wa Mushannafâtuh. Kairo: Dar al-Salam.
Selengkapnya...